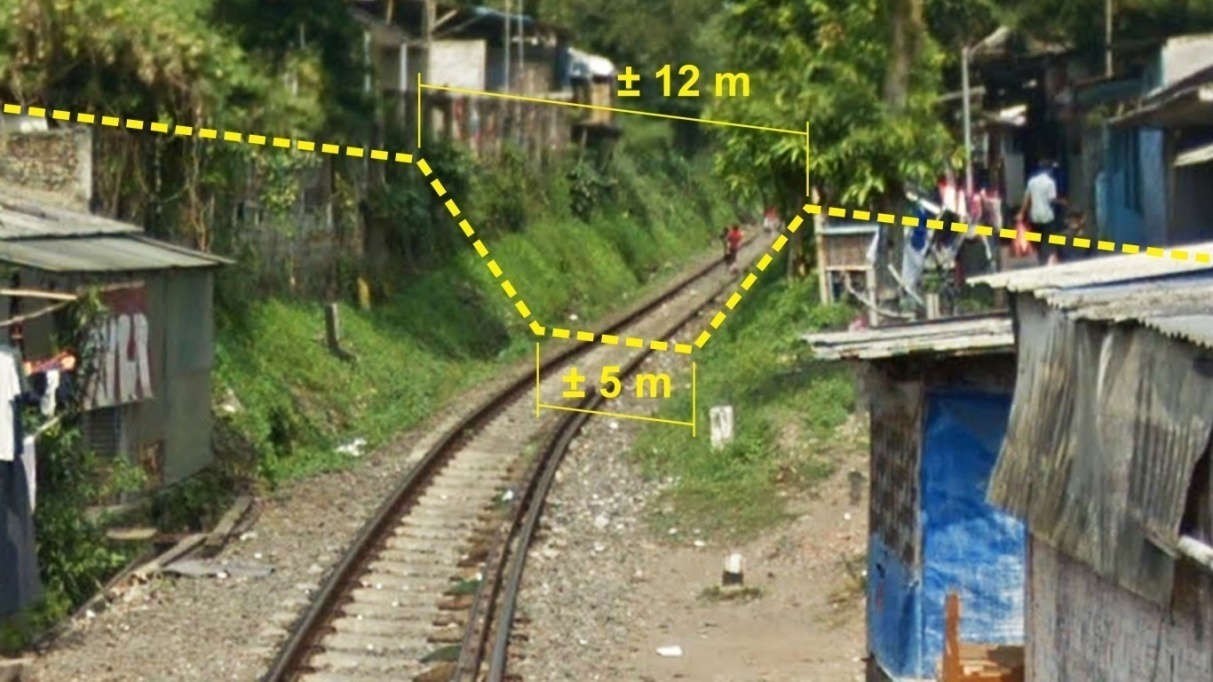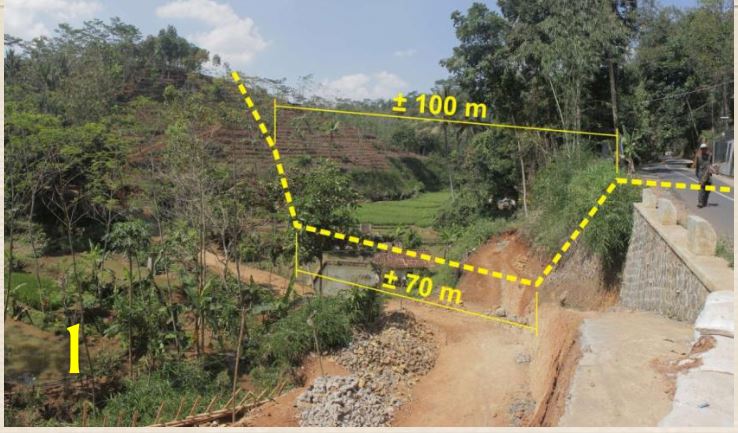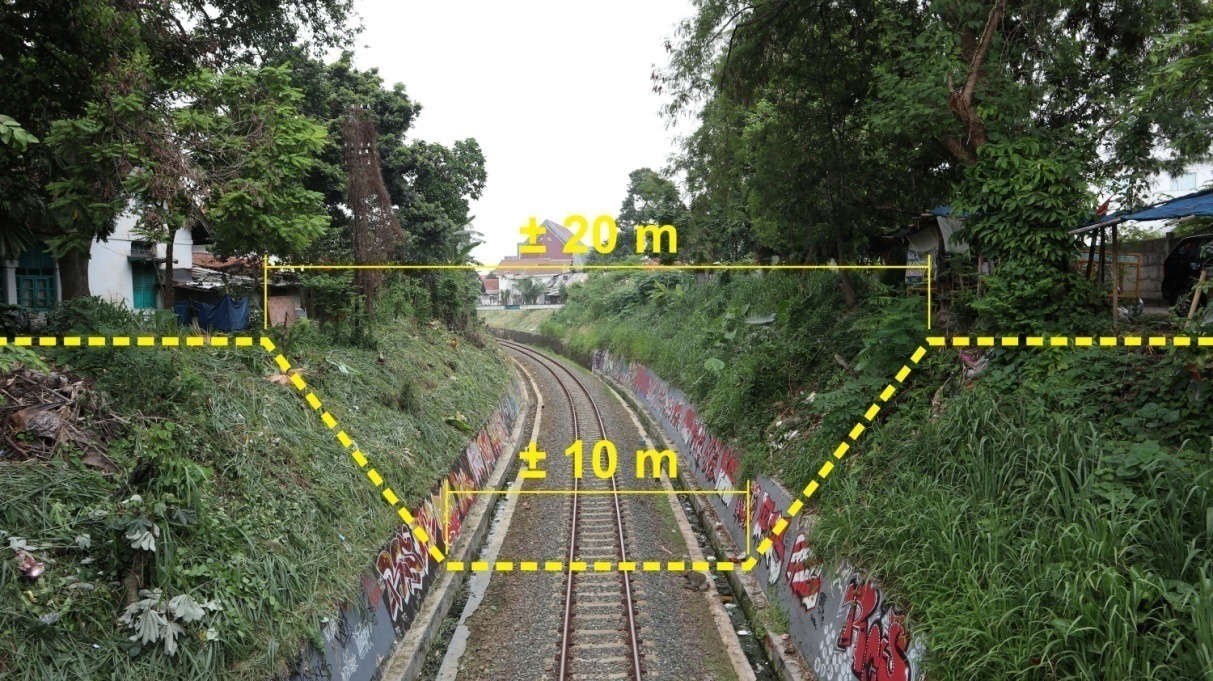Sumber : Rekontruksi Kota Galuh Pakwan (1371-1475 M) Dan Kota Pakwan Pajajaran (1482 - 1521 M), Budimansyah, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Bandung 2019
Di tengah gempuran isu global seperti krisis pangan dan kerusakan lingkungan, kita kerap menganggap solusi hanya bisa datang dari teknologi canggih. Padahal, bila kita menoleh ke masa lalu — ke jantung peradaban Sunda klasik, Kerajaan Galuh dan Pajajaran — kita akan menemukan warisan luar biasa berupa teknologi pangan dan konservasi yang sangat maju untuk masanya, bahkan relevan hingga kini.
Lebih dari Peladang Berpindah: Bukti Perubahan Sistem Pertanian
Citra masyarakat Sunda kuno sebagai peladang berpindah (huma) memang dikenal luas, dan masih hidup dalam komunitas adat seperti di Banten Kidul (Indrawardana, 2012). Namun, kesimpulan ini perlu direvisi jika kita mencermati naskah-naskah kuno dan prasasti yang menunjukkan bahwa pertanian sawah dan pengelolaan air telah dikenal jauh sebelum abad ke-17.
Dalam Naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian (SSKK) yang ditulis pada tahun 1518 M, terdapat kutipan:
"Jaga lamun urang nyieun sawah, éta sangkan teu sangsara."
(Jika kelak kita akan membuat sawah, itu agar kita tidak hidup sengsara.)
Kata “sawah” di sini bukan kiasan, melainkan refleksi pemahaman masyarakat kala itu akan pentingnya ketahanan pangan, dan bahwa sistem pertanian menetap berbasis irigasi telah menjadi bagian dari praktik hidup mereka.
Kawali dan Sistem Irigasi Strategis
Pusat dari revolusi ini dapat ditelusuri ke Kawali, ibu kota Kerajaan Galuh di masa pemerintahan Prabu Wastukancana. Raja ini bukan hanya memindahkan pusat pemerintahan ke Kawali, tetapi juga melakukan rekonstruksi tata ruang kota yang monumental:
Memperindah kompleks Keraton Surawisesa
Membangun parit di sekeliling kota sebagai pertahanan sekaligus irigasi
Seperti tercatat dalam Prasasti Kawali I, Wastukancana disebut:
“... nu marigi sa-kuliling dayöh, nu najur sakala desa ...”
(yang membuat parit di sekeliling kota, yang menyuburkan seluruh wilayah...)
Dalam bahasa Sunda klasik, “parigi” (parit) dan “najur” (menanam) bukan sekadar kata, melainkan refleksi dari sebuah sistem pengelolaan air terpadu — di mana fungsi pertahanan, pertanian, dan pelestarian lingkungan menyatu dalam satu infrastruktur.
Parit Sebagai Teknologi Konservasi
Menurut Susilawati (2006), konservasi tanah dan air adalah kunci untuk menyelamatkan kehidupan. Maka jelaslah, pembangunan parit-parit oleh masyarakat Sunda masa itu merupakan bentuk rekayasa ekologis yang sangat sadar lingkungan. Ini bukan hanya untuk bertahan dari serangan musuh, tapi juga untuk mengatur distribusi air pertanian, mencegah banjir, dan menjaga kesuburan tanah.
Inilah yang oleh para ilmuwan modern disebut sebagai konsep ekohidrologi — pengelolaan ekosistem berbasis air, yang di masa lalu telah dipraktikkan secara intuitif oleh para leluhur kita.
Dari Wastukancana ke Sri Baduga: Estafet Visi Ekologis
Warisan Wastukancana tak berhenti di Kawali. Cucu beliau, Sri Baduga Maharaja, membawa warisan itu ke tingkat yang lebih tinggi di Pakuan Pajajaran. Di masa pemerintahannya (1482–1521 M), tercatat sejumlah infrastruktur monumental:
Parigi pertahanan Pakuan
Sang Hyang Talaga Rena Mahawijaya (waduk air)
Samida (hutan larangan untuk konservasi)
Semua itu dikisahkan dalam Prasasti Batutulis (1521 M) yang dibuat oleh putranya, Prabu Surawisesa, sebagai bentuk penghormatan setelah 12 tahun wafatnya sang ayah:
“Beliaulah yang membuat parigi (saluran irigasi) Pakuan… membuat samida, membuat Sang Hyang Talaga Rena Mahawijaya.”
Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dari Wastukancana hingga Sri Baduga, terjadi estafet visi besar tentang pengelolaan air, pangan, dan lingkungan hidup secara terpadu. Ini bukan sekadar strategi kekuasaan, tapi perwujudan falsafah hidup Sunda: silih asah, silih asih, silih asuh — saling berbagi pengetahuan, kasih, dan perlindungan — termasuk terhadap alam.
Jejak Masa Lalu, Pelajaran untuk Masa Kini
Dalam dunia yang semakin rentan terhadap krisis iklim dan bencana pangan, warisan Kerajaan Galuh memberikan pelajaran penting: bahwa ketahanan pangan tak selalu memerlukan teknologi tinggi, tetapi bisa tumbuh dari keselarasan antara manusia dan alam.
Parigi (saluran irigasi), sawah, samida, dan waduk — semuanya adalah simbol dari sistem berkelanjutan berbasis lokal yang berpandangan jauh ke depan. Kini, tugas kita adalah menggali kembali warisan itu, mempelajarinya, dan mungkin... menggunakannya kembali untuk membangun masa depan.